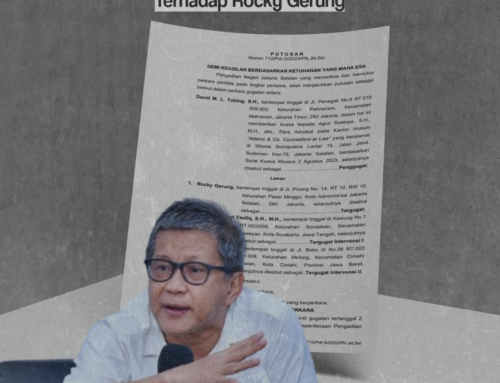Haris Azhar, SH, MA.
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation,
Pengajar Hukum dan HAM Universitas Trisakti dan Sekolah Tinggi Hukum Jentera Indonesia
Kuliah Umum Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Gunung Jati
Tangerang, 21 Juli 2018
Problem Kunci
“Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, Namun menegakkan equality before the law bukan tanpa hambatan. Bisa berupa hambatan yuridis dan politis, atau hambatan sosiologis dan psikologis. maka diadakannya kegiatan kuliah umum ini dalam rangka memberikan pencerahan terkait dengan solusi – solusi permasalahan tersebut.”
I. Dasar Hukum Konsep EBL dalam Peradilan di Indonesia
Equality Before the Law (selanjutnya, untuk memudahkan penulisan disebut EBL) adalah konsep yang sangat universal (berlaku dimana saja) dan tekstual bagi hukum. Secara universal EBL sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang mensyaratkan adanya hukum dan diberlakukan bagi setiap orang. Sedangkan tekstual, EBL tertulis dalam dokumen hukum yang induk aturan hukum yang menegaskan bahwa aturan hukum berlaku bagi semua orang ditempat hukum tersebut berlaku. Sebaliknya, dari sisi hukum, bisa dilihat bahwa hukum tidak membiarkan dirinya hanya untuk menguntungkan sejumlah pihak tanpa alasan yang sah dimuka hukum. Jika ada pengecualian maka hal tersebut mengkhianati konsep hukum.
Lebih jauh, salah satu unsur penting dalam hukum adalah substansinya yang patut memuliakan manusia, dalam bahasa Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) disebut sebagai Kehormatan Manusia (Human Dignity). Pada rejim hukum HAM, EBL adalah tema yang historis memiliki sejarah yang panjang. Berbagai peristiwa yang mengganggu nilai asasi manusia diakibatkan oleh praktik buruk dan penggunaan hukum sekedar untuk melayani kemauan penguasa. Hal ini kemudian menjadi dasar perlawanan berbagai korban, komunitas terdampak yang menyuarakan hak asasi mereka. Konsolidasi pengakuan HAM, misalnya, bisa dilihat dari kemunculan DUHAM pada 1948. Pada DUHAM tersurat kuat penolakan terhadap praktik diskriminasi (pasal 2). lebih luas, pada DUHAM digunakan “setiap orang…” artinya tidak boleh ada pengecualian hak terutama atas hak yang dibutuhkan bagi eksistensi manusia untuk hidup lebih martabat, termasuk menolak diskriminasi hukum.
EBL merupakan salah satu konsep untuk melawan diskriminasi, sebagaimana tergambar di atas. Upaya melawan praktik ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab Negara. Penjelasannya adalah, pertama, setiap negara atau otoritas harus mendasarkan kekuasaan dan pengaturannya berdasarkan pada hukum. Bagi Indonesia, hal ini bisa dilihat dari pasal 1 ayat 3 UUD 19945, yang menyatakan bahwa ‘Negara Indonesia adalah Negara Hukum’. Kedua, hukum tersebut harus berlaku bagi setiap orang, bukan sekedar warga negara. Pasal 28D menyebutkan bahwa ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum’. Sedangkan pasal 27 (1) menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dari kedua pasal diatas, bisa digambarkan bahwa ada perlakuan, yang seharusnya, sama baik bagi setiap orang maupun bagi setiap warga negara. Perbedaannya, pada pasal 27 (1) ada dalam bab Warga Negara dan Penduduk. Sementara pada pasal 28D berada pada bab HAM. Artinya, kesetaraan dimata hukum adalah sesuatu yang mendasar baik untuk tanggung jawab negara terhadap setiap orang yang berada di Indonesia, atau bahkan dalam konteks global (misalnya, disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, ‘..turut serta menjaga perdamaian dunia..”) dan bagi warga negaranya.
Turunan konstitusi dalam hukum atas kepastian EBL bisa dilihat dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 (1) yang menyebutkan ‘Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang’. Undang-undang ini menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan badan Peradilan yang berada dibawahnya seperti peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Termasuk peradilan khusus yang berada dibawah peradilan umum, seperti pengadilan HAM, pengadilan anak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan, pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan niaga (pasal 18, pasal 25 dan pasal 27). Selain Mahkamah Agung, juga secara sejajar Kekuasaan Kehakiman berlaku bagi Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sudah jelas bahwa Peradilan di Indonesia dalam hal ini melalui Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi mengemban tugas menjamin persamaan setiap orang di muka hukum (Equality Before the Law).
II. Praktik Peradilan di Indonesia
Praktik peradilan di Indonesia tidak menunjukkan gambar yang mulus dalam menjamin EBL terpenuhi bagi setiap orang di Indonesia. Pada bagian ini untuk menggambarkan problem EBL akan fokus pada sejauh mana peradilan dapat diakses bagi orang miskin atau bahkan peradilan justru menjadi sesuatu yang mengerikan bagi warga pada umumnya.
Sejumlah problem bisa dilihat, dimulai dari, Mahkamah Agung itu sendiri yang menjadi ujung penanggung jawab akses keadilan. Mahkamah Agung dalam upaya memastikan rencana kerjanya pada 2010 membuat ‘Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung 2010-20135’ yang memuat sejumlah problem, diantaranya,
“[..] dari penilaian organisasi atau Organizational Diagnostic Assessment (ODA) pada tahun 2009, kinerja lembaga peradilan tetap mendapat sorotan dari berbagai kalangan, antara lain mengenai informasi proses peradilan yang tertutup, biaya berperkara yang tinggi, masih sulitnya akses masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta proses penyelesaian perkara yang dirasakan masih sangat lama.” (hal. 3)
Demikian pula dengan masyarakat internasional seperti World Justice Project yang setia menguji performa peradilan di 46 negara, termasuk Indonesia, terutama pada konteks Access to Justice (Akses Keadilan). Survei yang dilakukan bertujuan untuk memotret bagaimana warga pada umumnya berurusan dengan masalah hukum, konflik-konflik hukum, penilaian dari warga atas proses penyelesaian konflik baik secara formal maupun informal serta pengalaman orang-orang yang tidak mencari bantuan hukum atau yang tidak bisa menyelesaikan masalah hukumnya. Temuan dari survei WJP teranyar (2017) adalah 26 persen dari responden mengalami insiden masalah hukum selama dua tahun terakhir; dari 26 persen di atas, terdapat dua persen di mana salah satu pihak mengalami kekerasan; dari jumlah 26 persen, hanya 8 persen yang mencari bantuan hukum (ke negara atau pihak ketiga) untuk penyelesaian masalahnya, sementara 92 persen tidak melakukannya; dari 8 persen yang mencari bantuan hukum hanya 79 persen yang mendapati penyelesaian atas persoalan hukumnya; dari yang selesai tersebut didapati hasil survei bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 1,98 bulan; mengalami kesulitan uang untuk membayar biaya penyelesaian masalah sebanyak 4 persen; menyatakan puas sebanyak 90 persen. Dari 8 persen tersebut ada 88 persen tahu kemana harus mencari nasihat hukum, 93 persen yakin akan mendapatkan hasil yang adil dan 78 persen mendapatkan bantuan dari ahli yang mereka butuhkan.
Sementara catatan dari kalangan masyarakat, terutama dari kalangan pekerja bantuan hukum dan organisasi advokasi Hukum dan HAM, didapati sejumlah masalah yang menggambarkan persoalan bahwa hukum dan proses peradilan bukan menjadi pelindung akan tetapi justru sebagai senjata yang mendiskriminasi warganya. Catatan ini dibuat melalui riset dan gelar perkata di 10 kota di Indonesia, proses ini dilakukan khusus sebagai respon atas maraknya, apa yang sering disebut sebagai kriminalisasi terhadap berbagai kalangan dari yang minoritas, rentan hingga bernuansa politis serta memiliki kepentingan bisnis. Catatan tersebut terdiri dari 3 bagian; pra-judicial process (sebelum memasuki pengadilan), proses pengadilan dan pembutkian, dan terakhir pada bagian vonis.
Pada bagian pertama, didapati temuan Bantuan Hukum yang tidak memadai, seringkali ditunjuk secara sepihak oleh oknum aparat penegak hukum untuk sekedar formalitas, atau ditunda pemberiannya. Bahkan dalam beberapa kasus bantuan hukum sama sekali tidak diberikan oleh aparat penegak hukum; Tidak ada Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), Tidak ada/penundaan surat penangkapan dan penahanan, Pelapor tidak jelas, Pasal yang disangkakan tidak jelas/dipaksakan; Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak diberikan, Rekayasa rekonstruksi kasus. Kedua, pada bagian Alat bukti, didapati sejumlah hal, sebagai ciri adanya kriminalisasi; Penyiksaan untuk pengakuan, Alat bukti dan barang bukti palsu, hanya menggunakan saksi penyidik, Saksi dari tersangka kasus yang sama. Ketiga, pada bagian vonis, dimana ciri-cirinya adalah Saksi meringankan (a de charge) tidak dipertimbangkan oleh Hakim, Hakim mengabaikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dicabut, Pertimbangan Hakim tidak sinkron dengan bukti yang diterima, Kesalahan penerapan hukum. (hal 13-18)
Terbaru adalah hasil dari Indonesian Judicial Reform Forum (IJRF) pada 2018, selain memotret sejumlah kemajuan institusional dari Reformasi Peradilan, juga masih mencatat sejumlah tantangan kedepan, sebagaimana digambarkan dibawah ini,
“Pembaruan peradilan masih dipahami sebagai tanggung jawab lembaga pengadilan semata dan belum dipahami sebagai tanggung jawab bersama seluruh lembaga peradilan, APH, advokat, lembaga pendidikan hukum, dan masyarakat sipil.
Pembaruan peradilan baru dirasakan menyentuh secara luas pada lembaga pengadilan, khususnya di MA. Pembaruan peradilan belum menjangkau pengadilan ditingkat bawah sebagai cermin pertama lembaga pengadilan di hadapan publik, serta lembaga-lembaga peradilan dan penegak hukum lainnya.
Pembaruan peradilan baru berjalan secara institusional khususnya di lembaga pengadilan pada beberapa area dan tingkatan strategis, dan belum menjangkau pada pembaruan hukum yang menyeluruh dan terintegrasi. Hal ini terjadi karena keadaan Cetak Biru Pembaruan Hukum sebagai pemandu, serta belum optimalnya sinergitas prioritas pembaruan hukum oleh masing-masing cabang-cabang kekuasaan (DPR, Pemerintah dan lembaga yudikatif).
Pelayanan peradilan masih diwarnai dengan adanya kriminalisasi, pungutan liar, biaya beracara yang tidak jelas, jadwal sidang yang tidak menentu, putusan yang tidak konsisten/inkonsistensi putusan, serta ketertutupan informasi untuk pihak di luar pihak yang berperkara.
Aparatur lembaga peradilan belum seluruhnya menyadari sumber mandat dan tujuan utama proses peradilan dan penegakan hukum.
Advokasi pembaruan peradilan yang dilakukan oleh masyarakat sipil belum sepenuhnya terstruktur dan menyentuh pada persoalan subtansial dengan menggunakan data-data lembaga penegak hukum secara maksimal.
Pelaksanaan dan hasil program-program pembaruan peradilan belum sepenuhnya diketahui secara luas oleh publik, melainkan terbatas hanya pada pihak-pihak yang intens memberikan asistensi program pembaruan.” (hal 18-19)
III. Kesimpulan dan Peluang EBL dimasa depan
Pemaparan di atas menggambarkan bahwa sejumlah temuan yang persistent (sudah berlangsung lama dan masih terjadi hingga hari ini); pertama, persoalan peradilan bukan hak yang merata dirasakan, bisa diakses atau terinformasikan bagi setiap orang di Indonesia. Dengan kata lain EBL tidak ter-ejawantahkan dengan baik dan otomatis hanya dengan modal norma hukum, institusi dan penyediaan Sumber Daya Manusia; kedua, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi peradilan yang menghambat pemenuhan dan pelaksanaan EBL seperti masalah ekonomi dan pendidikan warga sebagai penikmat peradilan, bahkan masalah pendidikan juga menjadi problem di kalangan para penegak hukum. Masalah politis juga muncul sebagai penekan berjalannya proses peradilan terutama pada kasus Kriminalisasi. Dalam pra Judicial process, melibatkan Polisi, di mana Polisi bekerja berdasarkan perintah komandan. Seringkali prinsip hukum kalah dari model perintah seperti ini. Sementara pihak pengadilan jarang berani melakukan koreksi atas kesalahan dalam penyidikan oleh Kepolisian. Artinya SDM Pengadilan belum secara total menjadi independen dan obyektif; Ketiga, masalah minimnya perubahan aturan (terutama hukum acara dalam berproses dalam peradilan). Meskipun di satu sisi disediakan Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan mengubah aturan main hukum, namun hal ini tidak menjamin tumbuhnya kepercayaan masyarakat atas hukum dan aksesibilitas masyarakat pencari keadilan untuk dengan mudah menggunakan dalam kepentingan haknya.
Lalu apa yang tersisa untuk membangun optimisme perlindungan EBL pada sistem peradilan? Ada banyak yang bisa dijadikan rekomendasi untuk mendorong optimisme melawan persoalan diatas. Beberapa diantaranya berupa, pertama, meningkatkan kualitas pekerja atau praktisi hukum yang memiliki wawasan baik dalam memahami prinsip hukum tanpa berbasis kepentingan politis atau ekonomi semata. Memiliki keberanian dan independen dalam menjalankan praktik hukum; memiliki kemampuan untuk melihat hukum yang harus berpihak pada yang membutuhkan, bukan sekedar yang mampu membayar atau menjadikan hukum sebagai obyek kontraktual (pelayanan jasa semata); memastikan semua syarat di atas berjalan merata pada profesi-profesi hakim, penuntut umum, advokat, polisi dll. Kedua, kontribusi akademisi dalam membangun diskursus yang mendalam, bernalar namun juga mudah dipahami oleh masyarakat, dalam konteks pendidikan publik. Bahkan jika perlu mendorong keberanian masyarakat untuk berargumentasi dan mengakses hukum. Ketiga, pengawasan pada mekanisme peradilan bisa berjalan, baik institusi-institusi pengawasnya (seperti komisi etik organisasi profesi, komisi-komisi negara dan badan pengawas internal institusi) maupun pengawas politis seperti DPR dan Presiden sebagai kepala negara bisa optimal dalam mengawasi dan mendesak transparansi institusi peradilan, untuk itu penting bagi masyarakat untuk dekat dan cerdas dalam proses politik yang menghasilkan kepemimpinan nasional, melalui Pemilu. Karena dengan hasil pemilu yang baik, bukan sekedar proses pemilunya yang baik, akan menghasilkan pemimpin yang sadar dan berpihak pada penegakan hukum.
***
Sumber bacaan dan data:
• Dr. Jaenal Aripin, MA, Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, 2010
• World Justice Project, Global Insight of Access to Justice, Findings from the World Justice Project General Population Poll in 45 Countries, 2018
• Mahkamah Agung, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, 2010
• KontraS, YLBHI, PSHK dkk, Kriminalisasi Modus dan Kasus-kasusnya di Indonesia, 2016