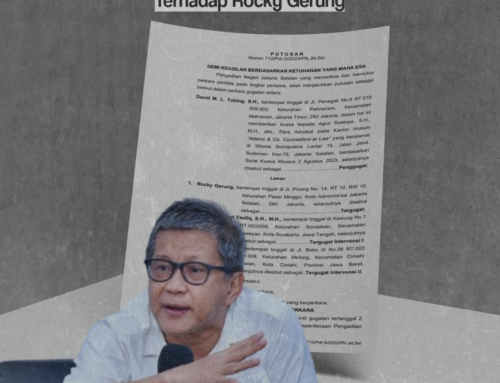Oleh Melani Aulia Putri Jassinta (Lokataru Foundation)
“….. kalau ada warga masyarakat yang merasa hak konstitusional dilanggar, pintu Mahkamah Konstitusi terbuka lebar-lebar untuk itu dan di situlah kita melakukan perdebatan hukum yang elegan dan saya kira bermartabat di situ ya.” Ujar Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej pada sidang pembahasan RKUHP tingkat pertama di Komisi III DPR RI beberapa saat lalu.
Ironis, di saat yang bersamaan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi justru telah kehilangan martabatnya akibat ‘tersandera’ oleh koalisi jahat para penguasa.
Penyanderaan Mahkamah Konstitusi (MK) ini dimulai sejak revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada 2020 lalu yang sarat akan konflik kepentingan terutama perihal masa jabatan hakim konstitusi. Konsep pengusungan hakim konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 (Hakim Konstitusi diusulkan oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Agung) ternyata turut menjadi celah bagi pemerintah (DPR-Presiden) untuk mengintervensi independensi MK.
Buntutnya, seluruh upaya-upaya penjinakkan MK itu kini menjadi alat politik balas budi oleh pemerintah untuk mengontrol dan mengambil alih Mahkamah Konstitusi. Puncaknya adalah pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR RI pada November lalu sebagai pertanda runtuhnya lembaga pengawal konstitusi kita.
Parlemen telah terang-terangan menginjak – injak konstitusi sebagai perwujudan kontrak sosial masyarakat dan pemerintah. Pemecatan Hakim Aswanto dengan dalih bahwa hakim MK itu adalah pertanda bahwa Indonesia di tangan penguasa hari ini tidak lagi layak disebut sebagai negara hukum. Hakim Aswanto diberhentikan bukan karena alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 23 UU MK. Alasan pemberhentian Hakim Aswanto telah dengan tegas dinyatakan oleh ketua Komisi III DPR RI, bahwa ia diberhentikan karena kinerjanya yang ‘mengecewakan’ karena dianggap menganulir produk-produk hukum yang dibuat oleh DPR.
Manuver politik pemecatan hakim konstitusi ini terjadi di tengah buruknya proses legislasi di Indonesia. Banyak produk hukum dilahirkan di atas protes keras dari seluruh lapisan masyarakat, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) pada 2020 lalu hingga pengesahan KUHP 2022 adalah cuplikan kecil dari abainya pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Penyusunan produk legislasi beberapa tahun kebelakang hampir seluruhnya cacat secara formil dan materil. Narasi-narasi diplomatis yang dilayangkan oleh DPR, “Jika tidak setuju dengan UU yang dibuat, silahkan gugat di MK” adalah bentuk arogansi yang ditunjukan secara terang-terangan oleh DPR.
Pemberhentian Hakim Aswanto adalah simbol kepemilikan MK oleh Pemerintah. Jika sudah begini, maka seluruh narasi arogan pemerintah yang menantang masyarakat menguji produk legislasinya di MK adalah gertakan yang ditujukan untuk memamerkan taring kepemilikannya atas MK. Pada akhirnya cita-cita pemerintah mengambil alih MK berhasil, bukan tanpa dasar melainkan retrogresi aktivisme yudisial di Mahkamah Konstitusi belakangan ini adalah bukti MK perlahan mulai menundukkan dirinya kepada koalisi jahat pemerintah.
Jika sudah begini, masih adakah peluang bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya melalui MK? Lagipun, tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan masyarakat temui ketika akan melakukan pengujian undang-undang di MK nanti, Ketua MK kah atau adik iparnya Presiden Jokowi?