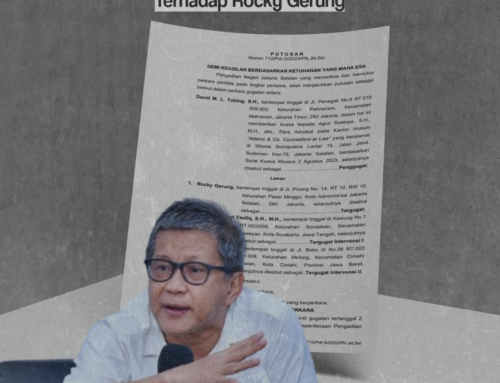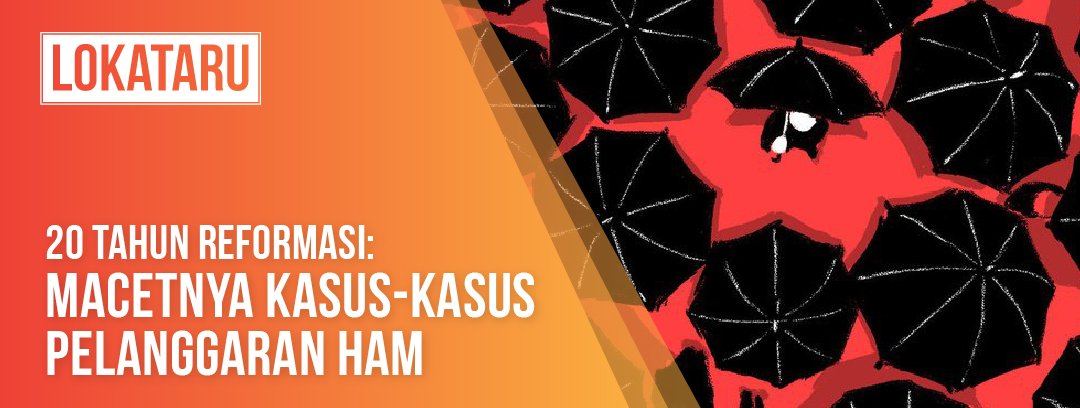
Setelah 20 tahun reformasi, bangsa Indonesia masih tertatih dengan keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan.
Peristiwa 12 Mei 1998 dikenang sebagai titik penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Pada peristiwa tersebut, empat mahasiswa Universitas Trisakti meninggal dunia, puluhan lain mengalami kekerasan, ratusan bahkan ribuan mahasiswa tunggang-langgang, berlarian panik memasuki kampus, dihujani peluru dan gas air mata.
Sebagian dari mereka melawan, melempar balik tabung gas air ke arah pasukan polisi dan tentara, yang berbaris meletuskan senjata, dari atas jembatan layang depan gerbang kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat.
Aksi 12 Mei memang aksi yang disusun lewat kepanitiaan yang terorganisir, didukung oleh Senat Mahasiswa Universitas Trisakti. Keempat korban tersebut bersama lainnya mempersiapkan aksi guna memastikan partisipasi mahasiswa seluas mungkin. Tujuannya satu: menyuarakan perubahan rezim penguasa Indonesia di bawah Soeharto, yang sudah berkuasa lebih dari 30 tahun, sejak 1967.
Aksi itu merupakan wujud ekspresi yang kontradiktif. Satu sisi suara perubahan sudah saling menguatkan dari pelbagai daerah di wilayah Indonesia. Di sisi lain, makin menguatnya suara perubahan tersebut justru makin meningkatkan pola pengetatan oleh militer Indonesia terhadap masyarakat sipil saat itu.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 11 itu, dari depan gedung Rektorat Sjarief Thayeb, dilanjutkan ke luar kampus dan kemudian diadang di depan gedung Pemda DKI Jakarta Barat (saat ini gedung tersebut sudah dihancurkan). Ia dilawan dengan desingan peluru, membuat para mahasiswa kembali ke kampus. Setelah enam jam aksi, adrenalin mahasiswa kembali naik, karena panik maupun melawan diperlakukan buruk, juga marah karena melihat rekan-rekannya berdarah.
Pada peristiwa 12 Mei, di dalam kampus Trisakti, situasi cukup tegang sekaligus kacau. Tegang karena seketika aksi yang semula dilakukan secara ekspresif, mendadak berujung kekerasan yang berdarah-darah. Mahasiswa kaget. Dalam situasi krisis, sekitar pukul 5 itu, muncul respons yang saling menolong sekaligus mengambil langkah preventif. Dari penanganan korban, tempat persembunyian yang aman dari desingan peluru, hingga rumor di dalam kampus bahwa penembak telah masuk wilayah kampus.
Malam harinya, masih pada tanggal yang sama, kedukaan semakin pecah ketika para korban dibawa ke rumah sakit, dan didapati mereka menjadi martir dari tuntutan perubahan rezim. Keesokan harinya, 13 Mei, sejumlah titik di Jakarta menjadi titik kumpul pelbagai massa yang marah, membakar, dan menjarah, termasuk di depan kampus Trisakti, Grogol.
Mereka memanggil mahasiswa untuk keluar bergabung dalam kemarahan tersebut. Sementara di kampus, pada saat itu menjadi situs kesedihan gerakan mahasiswa. Berbagai sivitas kampus lain datang dan hadir, berbelasungkawa sekaligus memompa semangat. Termasuk para politikus, cendekiawan, dan orang-orang populer dalam perlawanan terhadap Orde Baru.
Akan tetapi konsolidasi kemarahan yang paling penting adalah momen pemakaman mahasiswa di Tanah Kusir. Ribuan mahasiswa Trisakti hadir. Mereka tidak takut setelah sehari sebelumnya ditembaki. Ribuan pasang tangan bergantian mengangkat jenazah hingga ke liang lahat.
Usai tanah terakhir ditabur di atas jenasah, Om Boy, ayah Elang Mulia Lesmana, membuat pidato singkat bahwa kematian anaknya adalah titik tolak perjuangan perubahan bangsa. Bagi saya, teriakan Om Boy itu adalah jerit orisinal orangtua yang menuntut pertanggungjawaban bangsa atas peristiwa terhadap anaknya.
Peristiwa 12 Mei adalah bagian dari rangkaian panjang peristiwa yang menuntut perubahan terhadap rezim Soeharto. Pemerintahan Soeharto menerapkan kebijakan pengamanan militer, yang dikeluarkan oleh Wiranto, saat itu sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Kebijakan tersebut diterapkan sejak 1997 untuk pengamanan Pemilihan Umum.
Imbasnya, peristiwa-peristiwa demokratik dari masyarakat dan oposisi politik dihadapi kebijakan pengamanan yang represif. Karena itu penting melihat rangkaian panjang hingga terjadi peristiwa 12 Mei 1998, dan peristiwa-peristiwa sesudahnya.
Peristiwa sebelumnya adalah penyerangan kantor Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia di Menteng, yang dikenal sebagai peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli). Ia diikuti penghilangan orang secara paksa atas sejumlah mahasiswa, seniman, dan aktivis sepanjang 1997-1998. Kemudian, aneka tindakan kekerasan ABRI terhadap mahasiswa di pelbagai kota dan kampus (Medan, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Palembang, Makassar, dan sebagainya). kebijakan yang sama masih diberlakukan pada peristiwa Semanggi I (November 1998) hingga Semanggi II (September 1999).
Transisi Politik dan Dilema
Peristiwa 12 Mei, yang kemudian diikuti kejatuhan Soeharto pada 21 Mei 1998, menjadi momen awal proses transisi pada sejumlah hal di Indonesia. Secara lebih umum, ini dikenal sebagai “transisi demokrasi.”
Transisi ini upaya perubahan dari situasi yang muram di masa Soeharto ketika peran masyarakat dibuat minim. Masyarakat hanya dijadikan objek, dianggap cuma membutuhkan stabilitas harga-harga kebutuhan ekonomi serta dipaksa puas dengan pemenuhan ekonomi tersebut. Transisi yang dicitia-citakan adalah transisi menuju masyarakat yang lebih partisipatif dalam proses–proses kenegaraan.
Ada dua model perubahan yang saling tarik-menarik dalam masa transisi politik di Indonesia. Pasca-1998, terjadi pemerintahan transisi, dari Presiden Soeharto ke B.J. Habibie. Di masa Habibie, lahir sejumlah aturan hukum “baru” untuk menunjang proses transisi politik Indonesia. Salah satu tugas utama Habibie adalah menyiapkan pemilu yang demokratis, yang kemudian terjadi pada 1999.
Hanya dalam satu tahun, Indonesia sudah menjalani pemilihan umum presiden dan parlemen yang cukup demokratis. Sesudahnya adalah perubahan besar pada amandemen konstitusi Indonesia. Hampir semua pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang puluhan tahun digunakan oleh Orde Baru, diamandemen alias diperbaiki. Konsep-konsep baru yang menumbuhkan institusi baru pun diakomodasi dalam amandemen UUD 1945, yang berlangsung selama empat kali sejak 1999-2002. Institusi ini di antaranya Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi.
Hak asasi manusia mendapatkan tempat yang khusus dalam masa-masa awal transisi politik. Hal ini lumrah karena, pertama, proses transisi politik terjadi dengan pemantik peristiwa-peristiwa yang tergolong pelanggaran HAM, seperti peristiwa penembakan mahasiswa, penculikan dan penghilangan aktivis, dan kerusuhan Mei.
Pertama, alasan lain tuntutan perubahan karena banyak peristiwa pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. Ketiga, aktor-aktor perubahan dan pengusung demokrasi adalah korban dan pembela HAM. Karena itu isu HAM secara konseptual dan secara operasional merupakan tema yang tak terhindarkan dalam pengalaman negara-bangsa Indonesia.
Tempat khusus bagi HAM di Indonesia dituangkan lewat berbagai sarana. Pertama, dalam konstitusi, perubahan bab Hak Asasi Manusia menjadi semakin padat pada pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Melalui amandemen tersebut, perlindungan HAM dilekatkan dengan jaminan penegakan hukum.
Kedua, pengakuan HAM dalam konstitusi didahului lewat pengakuan atas Deklarasi Umum HAM 1948 melalui Ketetapan MPR Nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia (PDF). Ia kemudian diikuti lahirnya UU 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (PDF).
Pada saat bersamaan Indonesia meratifikasi konvensi internasional menentang penyiksaan dan praktik tidak manusiawi lainnya. Semua tindakan ini bentuk perlawanan terhadap trauma bangsa yang digulung kekerasan dan kejahatan atas kemanusiaan.
Ketiga, tempat bagi HAM semakin terasa lewat muncul atau menguatnya pelbagai institusi. Wewenang Komnas HAM diperkuat sebagai penyelidik—menjadi bagian dari penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi didirikan untuk menguji hak konstitusional warga negara dalam sebuah undang-undang; menjadi pengadilan uji norma HAM.
Perubahan-perubahan tersebut tidaklah mulus. Dalam proses transisi politik itu terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM baru, kekerasan dan kejahatan lain.
Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan norma HAM, yang sedang didiskusikan dan dirumuskan, tak serta merta menjadi norma internal individual setiap orang atau dalam kebijakan institusi.
Misalnya, pada 1999 ketika kita baru setahun memulai reformasi untuk menyiapkan Pemilu, di Timor Timur (sekarang Timur Leste), terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Peristiwa ini perintah langsung dari Wiranto sebagai Panglima ABRI saat itu.
Itu sungguh kontradiktif. Pada 1998, sesaat setelah Soeharto mundur, Wiranto sendiri yang datang ke Aceh dan meminta maaf atas praktik Orde Baru di Serambi Mekkah. Namun, pada November 1998, Wiranto pula yang bertanggung jawab atas penembakan mahasiswa di kampus Atma Jaya Jakarta.
Kontradiksi lain adalah konflik berdarah berbasis etnis dan agama, yang terjadi bersamaan dengan transisi politik. Konflik ini di antaranya terjadi di Maluku, Poso, Sampit, dan Sambas. Peristiwa-peristiwa ini terjadi antara 1999 hingga 2002-2003.
Beberapa dari daerah konflik itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki keadaan. Kekerasan komunal tersebut sangat melukai dan membekas bagi orang yang terlibat konflik maupun para korban. Warga sipil, terutama yang diidentifikasi sebagai bagian dari etnis atau agama tertentu dalam konflik di Maluku dan Poso misalnya, bukan sekadar dipaksa menjadi pengungsi, tetapi juga sebagai korban jiwa, luka, dan kehilangan harta benda.
Sesudah peristiwa Timor-Timur, Indonesia memiliki pengadilan HAM yang didirikan lewat UU 26/2000. Akan tetapi, pengadilan HAM bukan menghukum, justru membebaskan para pelakunya.
Munir, aktivis dan advokat HAM, justru dibunuh lewat operasi yang diduga kuta dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN), saat itu dipimpin oleh A.M. Hendropriyono. Ironisnya, pembunuhan Munir dilakukan pada 6 Oktober 2004, tanggal yang bersamaan ketika UU 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi disahkan. Munir adalah pejuang yang gigih mengusut keadilan dan akuntabilitas atas korban Orde Baru seperti kasus Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, dan penculikan aktivis 1997-1998.
Undang-undang soal komisi kebenaran dan rekonsiliasi itu dibuat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ironisnya, UU ini mensyaratkan pemulihan hak korban bisa diberikan jika korban memaafkan para pelaku kejahatan. UU ini dibatalkan oleh MK pada 2007.
Setelah 20 reformasi, kita masih menyaksikan berbagai peristiwa dan tumbuhnya angka korban dan penderitaan warga. Selain pelbagai kasus di atas, kita juga perlu melihat dan merefleksikan temuan-temuan dari organisasi-organisasi seperti KontraS, LBH, Konsorsium Pembaruan Agraria, dan Komnas Perempuan, serta pelbagai organisasi di daerah.
Mereka mencatat situap tahu ada rata-rata 40 sampai 60-an kasus individu yang disiksa ketika ditahan polisi; aktivis petani, masyarakat adat, dan hak atas tanah rentan diserang oleh preman dan dipenjara karena dipidanakan oleh perusahaan; ribuan masyarakat harus memobilisasi diri untuk mempertahankan tanah (adat); ratusan anak-anak perempuan menjadi objek perdagangan orang ke luar negeri karena dilema orangtua yang miskin.
Refleksi atas Situasi HAM, 20 Tahun Terakhir
Dokumentasi ringkas dalam 20 tahun terakhir memberikan sejumlah catatan.
Pertama, peristiwa pelanggaran hak asasi manusia terjadi bersamaan dengan para pengusung agenda reformasi bekerja untuk memperbaiki konstitusi dan hukum. Ketika mereka bekerja, di lapangan, ada warga dan masyarakat yang diterpa peluru, serta menjadi bulan-bulanan kebencian antar-kelompok.
Kedua, masa reformasi tidak memberikan keadilan dan pemulihan terhadap korban dan masyarakat secara lebih luas. Dampaknya, para korban terpecah dalam dua kutub: korban yang masih gigih membela hak mereka; ada juga korban yang telah lelah, dan sebagian ada yang meninggal, atau memilih diam.
Ketiga, masa awal reformasi cukup memukul penjahat HAM, tetapi masa sepuluh tahun kedua, para pelaku kembali menapaki karier politik dan ekonomi karena institusi dan norma HAM tak cukup ampuh menghukum mereka.
Keempat, norma-norma hukum HAM tetap diabaikan sehingga melahirkan laju kejahatan baru.
Bangsa ini, setelah 20 tahun reformasi, masih tertatih dengan keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Bakal sia-sia jika upaya apa pun yang dilakukan hari ini dihadapi oleh rezim yang diisi orang-orang yang berlumuran darah. Tugas negara sangat sederhana: ia harus berani dan bekerja mengembalikan hak warga dan menjamin perlindungan hak asasi manusia.
Daftar kasus dan pelanggaran HAM sangatlah banyak, bukan hanya dari masa Orde Baru, tetapi selama 20 tahun terakhir. Jika kita gagal menyelesaikan kasus-kasus ini, kohesi sosial dan integritas negara bakal cepat menyusut.
========
Penulis : Haris Azhar
Editor : Fahri Salam