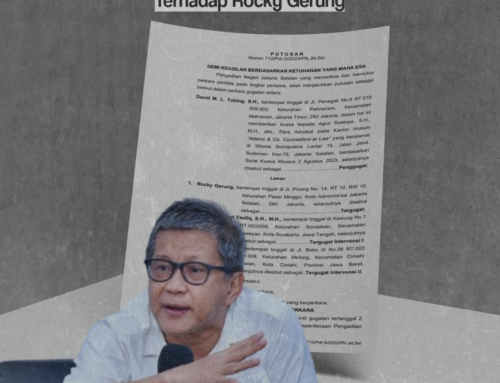Lokataru Foundation, 17 Februari 2021 – Setelah ramai dihujat publik karena minta dikritik, pemerintah melempar wacana revisi UU ITE. Senin (15/2) kemarin, Presiden Joko Widodo meminta DPR untuk merevisi pasal karet UU ITE yang dianggap mudah diinterpretasikan secara sepihak. Jokowi juga meminta Kapolri meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam implementasi UU ITE di lapangan. Menko Polhukam Mahfud Md kemudian mengumumkan bahwa pemerintah tengah mendiskusikan revisi UU ITE secara intensif.
Dukungan dan apresiasi terhadap langkah pemerintah untuk merevisi UU ITE terus mengalir dari masyarakat. Selama ini UU ITE memang banyak diamini sebagai sumber kemunduran demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, revisi ini bahkan seperti digadang-gadang sebagai juru selamat demokrasi Indonesia yang baru-baru ini dikabarkan dalam keadaan terburuk selama 14 tahun terakhir oleh The Economist Intelligence Unit.
Lokataru Foundation melihat tiga hal yang bisa disikapi dari pernyataan Presiden. Pertama, pernyataan Presiden di tengah tekanan ini dapat dilihat sebagai upaya memperbaiki wajah demokrasi yang lesu selepas indeks demokrasi Indonesia dinyatakan menurun. Mungkin ini jadi momentum bagi Kapolri baru yang katanya hendak berpegang pada prinsip restorative justice, untuk sesegera mungkin memulihkan korban-korban kriminalisasi pasal karet dari beleid yang ditandatangani 2011 silam. Hal ini untuk menunjukan penyesalan atas praktik pemidanaan via UU ITE selama ini.
Apakah cukup sampai disitu? Sayangnya tidak.
Hal kedua dan yang tak kalah penting menyangkut kualitas masyarakat sipil itu sendiri. Naasnya, akibat frekuensi serangan pemerintah terhadap kebebasan sipil yang amat masif di dalam keseharian, masyarakat kerap luput melihat bahwa mereka sesungguhnya juga punya kontribusi yang tak sedikit terhadap kemunduran demokrasi.
Sejak 2018, dua kelompok terbesar pelapor UU ITE adalah pejabat publik dan masyarakat sipil. 35,9% pelapor adalah kepala daerah, menteri, aparat keamanan, dan pejabat publik lainnya. Sedangkan pelapor dari masyarakat sendiri tercatat mencapai 32,2%. Di tahun 2019, data yang dihimpun SAFENet menunjukkan setidaknya ada 3100 kasus UU ITE yang dilaporkan. Data Koalisi Masyarakat Sipil (ICJR) menunjukkan sepanjang 2016-2020, tingkat conviction rate kasus pasal karet mencapai 96.8% atau 744 perkara. Sedangkan tingkat pemenjaraan mencapai 88% atau 676 perkara.
Perbedaan tipis antara jumlah pelapor warga dan pemerintah membuktikan bahwa masyarakat sipil sendiri gagal memahami dan mempraktekkan kebebasan berekspresi. Tak ubahnya tabiat pemerintah, semangat memenjarakan lawan bicara nyatanya ikut lestari di masyarakat. Masyarakat sipil masih alergi terhadap kritik dan perbedaan pendapat yang, tragisnya, dibiarkan oleh pemerintah yang nampak meraup untung dari konflik warga yang berlomba-lomba mempolisikan sesamanya. Di momen politik besar seperti Pemilu atau Pilkada, kecenderungan ini melonjak berkali lipat. Sepak terjang buzzer sesungguhnya tak lebih dari efek samping dari kondisi mendasar ini: saat mental gerombolan warga senantiasa memandang lawan kubunya sebagai pihak yang mesti dibungkam dengan segala cara.
Keberpihakan dan diskresi selektif polisi dalam menangani kasus pasal karet tak dapat dipungkiri, namun hal ini turut menegaskan kegagalan masyarakat dalam menghadapi silang pendapat di ruang publik. Hal ini tercermin dari keluhan yang sering muncul manakala ada kubu yang ‘tak sukses’ mempolisikan lawannya lantaran adanya tebang pilih dalam penegakan hukum, alih-alih mempersoalkan keberadaan kriminalisasi itu sendiri. ‘Wabah’ anti demokrasi ini menjangkiti banyak pihak: baik pendukung rezim maupun oposisi, ormas, hingga akademisi.
Hal ketiga, merevisi pasal karet belaka kami nilai tak akan banyak mengurangi kemampuan negara dalam mengkriminalisasi warga. Ini bukan hanya soal dokumen hukum semata; tetapi kemampuan pemerintah (termasuk warganya) yang masih dipertanyakan saat berjumpa dengan kritik di ruang publik. Lagipula, pemantauan Lokataru Foundation selama setahun terakhir menemukan bahwa negara masih memiliki seabrek perangkat hukum lain yang dapat digunakan sesuai kebutuhan; seperti pasal penghasutan, keonaran hingga pelanggaran aturan kerumunan. Pasal penghinaan terhadap mata uang rupiah pun bisa dipakai untuk membungkam masyarakat sipil seperti kasus Manre, nelayan Kodingareng, Makassar yang merobek ‘amplop’ ganti rugi dari PT. Boskalis.
Tambah lagi dengan penggunaan Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP) yang kerap dipakai korporasi untuk memukul mundur perlawanan masyarakat atau penghilangan paksa dan pembunuhan ekstrayudisial di Papua. Jangan lupakan juga ‘senjata andalan’ lain pemerintah, seperti kriminalisasi hoax dan patroli siber yang masih berjalan. Melihat semua hal di atas, tanpa UU ITE pun kualitas demokrasi kita akan tetap mandek jika tidak terus mundur.
Pasal karet memang harus direvisi. Namun, kemunduran demokrasi di Indonesia tak bermula dan berakhir sampai disini saja. Ia bermuara pada masalah yang lebih mendasar; tak hanya menyangkut pemerintah yang mendesain dan menggunakan perangkat hukumnya untuk menghajar warga, tapi juga mengendap dalam watak masyarakat sendiri, yang diam-diam menolak demokrasi yang mensyaratkan kebebasan berekspresi untuk semua.
Mirza Fahmi (Manajer Program Lokataru Foundation)