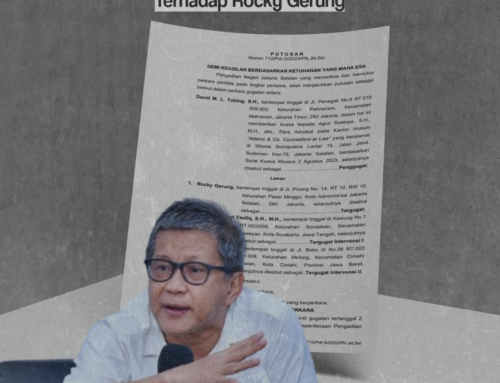Kita semua tentu mengecam serangan terorisme yang terjadi secara berturut turut dalam dua minggu terakhir ini; peristiwa di Rumah Tahanan Mako Brimob 9 Mei 2018, yang kemudian diikuti dengan serangan peledakan bom di tiga gereja di Surabaya (Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta) pada 13 Mei 2018 serta penyerangan Kantor Polda Riau pada 16 Mei 2018. Doa, kekuatan, dukungan dan solidaritas kita hadirkan bagi para korban dan keluarga, baik dari masyarakat ataupun anggota
kepolisian.
Rangkaian peristiwa ini berada di luar akal sehat dan mencederai kemanusiaan kita semua. Kewibawaan Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai bangsa yang besar dipertaruhkan. Mampukah kita melawan segala bentuk kekerasan, serangan terorisme, dan segala bentuk intoleransi dengan cara yang beradab, bermartabat dan menyeluruh. Ataukah sebaliknya, apakah kita akan memilih melawan dengan cara–cara pintas melawan hukum, yang menyalahkan dan mendelegitimasi hak asasi manusia, dan cara-cara yang justru dapat menafikan perbedaan dan keragaman yang kita percayai sebagai syarat kehidupan berbangsa. Tentu bukan pilihan terakhir yang kita harapkan. Cara-cara instan dan reaksioner semacam ini dikhawatirkan justru akan semakin mereproduksi rantai kekerasan, melemahkan langkah–langkah kontra radikalisasi dan upaya–upaya deradikalisasi terhadap benih ekstrimisme lainnya, serta semakin memperbesar polarisasi di tengah masyarakat.
Kami memahami kegentingan situasi hari ini dan dampak dari tindakan keji yang dilakukan oleh para pelaku terhadap korban dan masyarakat. Kami pun memahami dilema dan tantangan yang dihadapi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam memerangi terorisme. Oleh karenanya, tetaplah penting untuk memastikan langkah–langkah yang menyeluruh dan bermartabat dalam menyikapi masalah ini. Janganlah kita mencari jawaban dan solusi reaktif yang mendelegitimasi HAM, atau bahkan justru menjadikan HAM sebagai “kambing hitam” sebagai hambatan dalam memberantas kejahatan terorisme, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, mantan anggota TNI, AM. Hendropriyono, Ketua DPR Bambang Soesatyo atau politisi lainnya.
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami memberikan sejumlah catatan kritis dan
rekomendasi sebagai berikut:
Pertama, HAM adalah prasyarat mutlak dalam upaya penanggulangan terorisme. Prinsip- prinsip HAM telah diadopsi dalam pasal-pasal konstitusi kita, sehingga menyalahkan HAM dalam penanganan terorisme adalah pandangan yang reaktif, tidak proporsional, dan tidak memiliki justifikasi. Pernyataan ini mengabaikan berbagai faktor yang bersifat kompleks dalam persoalan terorisme. Dalam tatanan negara hukum yang demokratis, konsepsi hak asasi manusia telah memberikan standar dan pendekatan yang bisa ditempuh ketika ada atau terjadi pertentangan antara kepentingan publik dan hak seseorang, asas necessitas dan proporsionalitas harus dijadikan ukuran dalam mengatasi masalah tersebut. Hasil uji dari pendekatan tersebut akan menghasilkan sejauh mana margin apresiasi kita sebagai bangsa terhadap HAM. Namun, beberapa hak individual yang bersifat non-derograble, seperti hak untuk bebas dari penyiksaan tidak dapat dikurangi sedikit pun. standar-standar HAM akan dapat meminimalisir risiko munculnya praktik penyiksaan, salah tangkap, penahanan sewenang-wenang, miscarriage of justice dan pelanggaran HAM lainnya. Dalam konteks inilah maka parameter HAM akan menguji apakah kita mampu memerangi terorisme dengan cara yang bermartabat dan akuntabel, atau kita hanya mampu menjadi bangsa yang bersikap “barbar” yang mengabaikan standar hukum dan HAM sebagaimana pernah terjadi di masa Orde Baru.
Kedua, perumusan yang lebih komprehensif dalam strategi dan pendekatan yang lebih preventif dan mitigatif dalam memerangi terorisme patut dikedepankan. Menjadikan revisi UU Terorisme sebagai satu-satunya “pil ampuh” yang dianggap akan mampu menghentikan tindakan terorisme dan menjadi penyebab tunggal gagalnya pencegahan atas 5 (lima) peristiwa tindakan terorisme dalam dua minggu ini tidak sepenuhnya tepat. Revisi undang-undang, apalagi yang mengurangi hak warga serta menambah kewenangan Negara untuk membatasi hak perlu kita letakkan dalam kerangka reformasi hukum yang lebih luas. Perihal tidak memadainya hukum harus diuji berdasarkan praktik-praktik penerapan norma dan hukum itu sendiri yang selama ini dilakukan oleh penegak hukum, termasuk menguji apakah kewenangan upaya paksa saat ini tidak memadai untuk menindak berbagai tindakan perencanaan, plotting, persiapan dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat yang diduga atau diidentifikasi sebagai anggota kelompok teroris tidak terjangkau oleh norma hukum yang ada.
Berkenaan dengan tindakan preventif oleh pemerintah, penting dilakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap kinerja aparat keamanan, penegak hukum, badan-badan intelijen negara dan juga instansi atau lembaga terkait lainnya, misalkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Kita harus mengevaluasi apakah selama ini pemerintah telah menerapkan atau membuat sebuah pencegahan dan penanggulangan yang efektif, terkoordinir yang berkontributif pada upaya kontra terorisme. Hal ini untuk pembelajaran atas kemungkinan kekurangan dan kelalaian baik langsung maupun tidak langsung dalam implementasi kebijakan kontra-terorisme selama ini, sehingga masalah tidak hanya ditumpukan pada aturan apalagi menyalahkan HAM.
Ketiga, mekanisme akuntabilitas dalam penangangan kontra-terorisme juga harus menjadi prioritas bila upaya penindakan atau upaya paksa aktor keamanan dikedepankan. Upaya paksa tetap harus mengikuti dan mempertimbangkan standar-standar HAM, khususnya guna mengeliminasi risiko munculnya penyiksaan, salah tangkap, penahanan sewenang-wenang, miscarriage of justice dan pelanggaran HAM lainnya sehingga dalam penerapannya hukum berjalan dengan seimbang. Termasuk perbantuan TNI dalam penanggulangan terorisme harus dipastikan mengacu pada UU TNI tidak boleh bertentangan dengan UU TNI, Pasal 7 ayat (2) dan (3) di mana pelibatan militer harus melalui keputusan politik, memastikan tidak ada tumpang tindih dan tidak merusak kerangka penegakan hukum yang ada, termasuk memastikan revisi UU Peradilan militer harus dilakukan. Hal-hal yang berkaitan dengan masa penangkapan selama 14 hari dan penyadapan harus diiringi dengan ‘safeguard” dan mekanisme akuntabilitas yang independen dan memadai agar tidak menimbulkan potensi-potensi kesewenang-wenangan yang justru dapat mengakumulasi atau mengentalkan benih-benih ekstremisme lebih lanjut.
Keempat, pemulihan atas korban tidak hanya sebatas pemulihan kepada korban dari aksi terorisme itu sendiri namun pendekatan dan pemulihan terhadap kelompok atau masyarakat terdampak, termasuk kelompok terduga pelaku maupun keluarganya yang selama ini belum dapat dipenuhi oleh negara seperti kewenangan yang dimiliki LPSK, BNPT, Kementerian Sosial atau lembaga lainnya yang terkait. Tindakan pemulihan ini tidak hanya akan dapat meminimalisir kebencian dan ujaran kebencian, namun juga dapat menjadi sebuah upaya deradikalisasi dan menaikkan kepercayaan kelompok masyarakat terhadap negara yang telah menjalankan penegakan hukum dan pemenuhan atas hak asasi manusia kepada masyarakatnya.
Kelima, dampak lanjutan dari terorisme telah terdeteksi dalam peristiwa belakangan ini, seperti diskriminasi, prasangka negatif terhadap identitas kultural tertentu, kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak, tidak dapat diatasi dengan prosedur
hukum semata. Pemerintah bersama partai politik, beserta elemen masyarakat sipil perlu mengedepankan contoh-contoh praktik kemanusiaan yang telah muncul dalam reaksi solidaritas yang diberikan oleh masyarakat terhadap para korban. Persoalan ini adalah persoalan jangka panjang yang hanya dapat diwujudkan jika upaya-upaya kita dalam menghadapi terorisme, kita tempatkan dalam kerangka nilai-nilai HAM dan Pancasila.
Keenam, terorisme yang berakar dari radikalisme dilakukan secara terorganisir serta memiliki pola yang sistematis dari tahap perekrutan, kaderisasi, hingga aksi. Artinya, strategi anti terorisme juga harus dilakukan dengan cara yang lebih menyeluruh dan mendasar, yang juga mencakup aspek sosial, pendidikan, dan budaya, dengan mengembalikan nilai-nilai bhineka tunggal ika yang saling menghargai, tanpa kekerasan dan tanpa diskriminasi terhadap perempuan.
Demikian pandangan ini kami sampaikan sebagai bagian upaya kontributif dalam menempatkan persoalan ini secara proporsional dan konstruktif, termasuk sebagai cara untuk terus mengingatkan pemerintah dan mengajak masyarakat untuk tidak terpecah belah dan
melawan terorisme dengan cara yang menyeluruh dan bermartabat.
Jakarta 17 Mei 2018
KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, Elsam, IMPARSIAL, PSHK, YAPPIKA, LBH APIK,
ICJR, Setara Institute, Amnesty International Indonesia, AJAR, WALHI,
PERLUDEM, KPA, Solidaritas Perempuan, LeiP, Yayasan Jurnal Perempuan, Karlina
Supelli, Franz Magnis Suseno, Haris Azhar, Suciwati