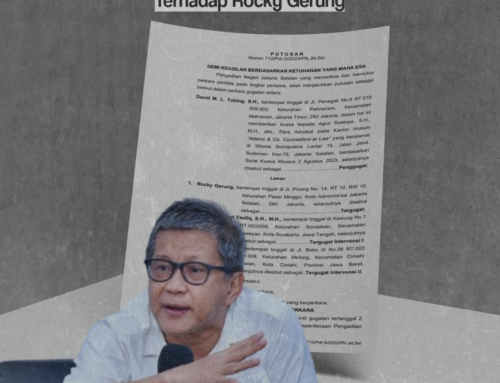Di tengah gelombang susulan pandemi COVID-19, DPR mengesahkan draft revisi Otsus dalam rapat paripurna Rabu kemarin (14/7). Di hari yang sama, 23 mahasiswa Universitas Cendrawasih ditangkap saat menggelar aksi duduk diam menolak Otsus di kampus Uncen dan Dok 9. Meski telah membubarkan diri, peserta aksi tetap didatangi dan dikejar aparat gabungan TNI & Polri.
Jelang rampungnya revisi, Majelis Rakyat Papua (MRP) turut memprotes minimnya keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam proses revisi – sebagaimana mandat UU Otsus itu sendiri – dan mengajukan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara soal perubahan kedua UU Otsus ke Mahkamah Konstitusi akhir Juni lalu. Namun, 3 Juli kemarin Mahkamah Konstitusi menunda sidang SKLN tersebut dengan pertimbangan pandemi COVID-19.
Badan Baru Minim Representasi
Pada UU Otsus terdahulu, Pasal 76 terkait pemekaran wilayah hanya memberi kewenangan persetujuan pemekaran kepada MRP dan DPRP. Kini Pasal 76 memiliki ayat baru yang memberi pemerintah pusat wewenang untuk memekarkan daerah di Papua. Selain itu, revisi UU Otsus menghapus kewajiban konsultasi terhadap MRP dan DPRP pada tahap rekrutmen anggota parpol baru penduduk Papua.
Revisi UU Otsus juga membentuk badan baru dengan fungsi harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di wilayah Papua (Pasal 68a). Tim tersebut diketuai oleh Wakil Presiden, yang tidak memiliki rekam jejak terkait Papua. Sedangkan masyarakat Papua hanya dapat mengirim satu perwakilan dari tiap provinsi sebagai anggota. Lagi-lagi Orang Asli Papua tak memiliki kendali atas badan yang diklaim dibentuk untuk perbaikan pembangunan wilayah Papua.
Tim baru ini juga tidak menyentuh persoalan utama dari ketegangan hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua, yakni krisis kepercayaan yang sudah amat kronis. Terbukti dari absennya rencana penyelesaian masalah HAM, rasisme struktural, serta kerusakan lingkungan hidup Papua.
Absennya representasi masyarakat Papua sudah terbaca sejak proses pembahasan revisi Otsus. Alih-alih diakomodir sebagai wakil masyarakat, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) acap diintai, direpresi dan ditangkap ketika melaksanakan tugas. November lalu, misalnya, Rapat Dengar Pendapat untuk mendengar aspirasi Orang Asli Papua digeruduk aparat. Total 54 orang tim dan peserta dibawa ke kepolisian dengan dugaan makar dan tak mematuhi protokol kesehatan.
Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menerbitkan maklumat yang melarang siapapun dalam RDP untuk “merencanakan atau melakukan tindakan yang menjurus tindak keamanan negara, makar, atau separatisme atau pun tindakan lainnya yang dapat menimbulkan pidana umum atau atau perbuatan melawan hukum lainnya dan konflik sosial.” Padahal, Maklumat Polri seharusnya bersifat internal dan tidak dapat menginstruksikan larangan apapun di luar jajaran kepolisian.
Kekerasan Terhadap Penolak Otsus Jilid II
Selama setahun terakhir, pemerintah konsisten menggunakan dalih pandemi untuk membungkam masyarakat sipil. Tidak terkecuali masyarakat Papua yang menolak Otonomi Khusus jilid dua dan Daerah Otonomi Baru (DOB). Modus lainnya adalah dengan berdalih demonstrasi tak berizin atau tidak mengirimkan surat pemberitahuan.
Pembubaran paksa aksi tolak Otsus Jilid II diwarnai dengan pemukulan dan tembakan. Pada Oktober 2020, demonstrasi tolak Otsus mahasiswa Uncen dibubarkan paksa oleh aparat gabungan Kodim 1702, Polresta Jayapura dan Brimob Polda Papua. Menurut Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay, satu orang massa aksi menderita luka tembak.
Aparat biasanya berdalih pengamanan atau dugaan provokator, namun jumlah massa yang ditangkap sangat berlebihan, dari 30 hingga 100 orang. Aparat gabungan yang dikerahkan dan alat pengamanan yang digunakan juga tak sebanding dengan jumlah demonstran. Pada November 2020, demonstrasi tolak Otsus Jilid II yang dihadiri ribuan massa Petisi Rakyat Papua (PRP) Wilayah Meepago dibubarkan. Sebelum massa datang, aparat Polisi dan TNI telah berjaga dengan senjata lengkap. Menurut juru bicara PRP, polisi merampas ponsel massa, mengancam, dan melakukan pemukulan. 100 massa dibawa aparat ke Polres Nabire.
Revisi Otsus: Satu Coreng Lagi Di Wajah Rezim Jokowi
Di tahun ketujuh rezim ini berkuasa, makin tidak pantas rasanya menyandingkan ‘demokrasi’ berbarengan dengan menyebut nama Joko Widodo. Kami menilai revisi Otsus ini sangat bermasalah dari hulu ke hilirnya dan tidak sepantasnya diloloskan menjadi Undang-undang. Tidak ada deliberasi dan partisipasi yang sehat dalam perumusan revisi, dibarengi dengan terus dihembuskannya kampanye ultra-nasionalis mengenai keutuhan NKRI yang penuh teror dan ancaman. Diskusi Otsus kerap dihambat oleh pembubaran, serangan digital dan teror, yang hingga hari ini tak pernah diusut siapa pelakunya. Sementara itu, kritik lembaga resmi seperti MRP dan masyarakat sipil di lapangan selalu direspon dengan hantaman aparat. Pengesahan revisi UU Otsus di tengah gelombang pandemi terbaru ini tidak lain merupakan aksi penyelundupan hukum, sebuah cela yang serius dalam demokrasi. Revisi UU Otsus merupakan legalisasi atas dominasi dan eksploitasi “Jakarta” terhadap Papua, dan segenap masyarakatnya.
Wajar apabila masyarakat Papua kian geram dengan pemerintah. Sejak pencetusannya, aspirasi otentik mereka menjadi hal yang paling tak diinginkan pemerintah untuk muncul ke permukaan. Kompleksitas persoalan Papua hari ini, mulai dari perampasan lahan, rasisme struktural, pembunuhan ekstra-yudisial, pelanggaran HAM masa lalu, perusakan lingkungan, sampai aspirasi kemerdekaan yang melulu direspon dengan brutal oleh pemerintah, tak akan tuntas dengan revisi Otsus. Justru sebaliknya, kekecewaan dan amarah masyarakat, seperti api, akan terus membara di bawah permukaan. Sampai tiba saatnya ia meledak. Melihat tabiat rezim, besar kemungkinan ekspresi kemarahan ini kelak akan kembali disambut dengan kekerasan.
Lokataru Foundation